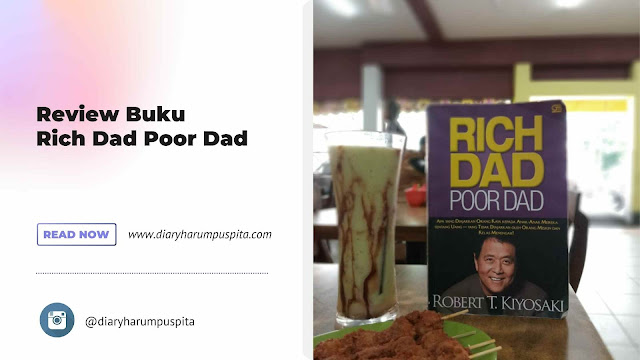Kupikir Dia Racun, Ternyata Amunisi
Bagaimana cerita ini bisa
dimulai? Ah, sebenarnya itu sudah sangat lama. Aku berusaha mengorek penggalan
masa silam yang paling samar tentang hadirnya lelaki menemukanku lebih dulu. Kupikir
pun begitu, aku biasanya menemukan orang lebih dulu dikarenakan aku yang sering
menyembunyikan identitas dari khalayak ramai.
Bagiku, aku adalah orang biasa. Segala
pencapaian yang kupunya kalau bisa nggak usah orang tahu. Aku takut mereka akan
minder dengan cara berpikirku yang tidak bisa diam, pantang jalan di tempat,
dan bawaannya selalu ingin berkembang. Jika kedapatan aku terbengong enggak
karuan, rasa stress itu menghampiriku dan malah membuatku menjadi sakit.
Namun ternyata, bukan kemampuan
otak yang tidak berpikir membuatku sakit melainkan mengenali kecerdasan
emosionalku yang paling buruk. Padahal aku adalah salah satu makhluk paling
perasa. Saking perasanya, kupendam sendirian bersama ruang yang membisu. Hingga
rasa sakit itu terkadang menjelma menjadi penyakit aneh. Bahkan tak mampu
kutuliskan bentuk perasaanku yang tak terbentuk sekalipun. Bertahun-tahun
kujalani, hingga akhirnya aku bertemu dengan ia. Si makhluk dengan segala
pemikirannya yang acap kali tak jauh berbeda dengan lingkungan terdekatku.
Ternyata, kami sungguh berbeda. Dia
dengan Pemikirannya dan aku dengan Perasaanku. Sama-sama sering berpikir dengan
pikiran dan perasaan masing-masing. Aku yang tak ingin mengatakan bagaimana
perasaannku, berharap dia akan mengenali perasaanku dan dia dengan keegoannya
seolah tidak terjadi apa-apa. Emang bisa interaksi antara lawan jenis dalam
waktu yang lama? Sungguh itu sangat sulit, manusia yang paling berdampak adalah
si pemilik perasaan lebih dulu. Entah aku atau dia, aku pun enggak tahu. Katanya
lelaki itu lebih gampang jatuh cinta, sementara perempuan perlu waktu untuk
mencintai seseorang.
Racun itu bernama ketidakpedulian dengan perasaan
Kenapa orang bisa sakit? Hal yang
paling pasti adalah tingkat imunnya yang paling rendah. Namun kebanyakan rasa
sakit itu datang karena pemikiran dan pemikiran yang membuat cemas itu pula
sering kali tidak disadari.
Flahsback
Pagi itu dokter itu memarahiku,
melalui sorot matanya aku langsung mengeluarkan air mata sesenggukkan. Ia
memang tidak bertanya padaku seperti perempuan pada umumnya karena ia merupakan
dokter pria.
“Kamu enggak bisa bohong!
Seharusnya kamu makan lebih congok dengan
obat-obatan ini bukan malah sebaiknya. Sebanyak apapun obat yang kami beri,
jika jiwamu sakit akan tetap sama saja. Enggak ada gunanya,” ucapnya lantang
kemudian meninggalkanku di ruangan itu bersama perawat yang berusaha berbicara
padaku.
Anehnya, aku tidak menyadari
bahwa obat paling mujarab untukku yang sakit bukanlah Paracetamol atau
Amoxillin, ternyata ruang bercerita dengan orang-orang tertentu. Tipe si
manusia perasa itu ternyata hanya butuh ruang bercerita untuk mengobati jiwanya
yang tengah terluka.
Ternyata selama ini aku melukai
diriku sendiri atas dasar takut berdosa. Takut berdosa mengingat manusia yang
mengitari mimpi panjangku. Kusiksa diriku sendiri dengan menolak perasaanku
sendiri, menolak perasaan aku cenderung memikirkannya, serta menolak kebahagiaan
yang datang padaku. Tak usah basa-basi, kutolak rasa cinta yang Allah beri
padaku dan ternyata itu yang membuatku sakit hingga kurus kering.
Hatiku sungguh sangat buta, aku
lebih memilih beranjak pada masa depan yang belum pasti. Kusampaikan pada
diriku bahwa yang pertama ia jelas bukan mahramku dan kedua di hatinya bukan
aku yang diinginkannya. Aku sungguh egois sekali bukan, sebagai perempuan siapa
yang tidak ingin dijadikan sebagai ratu di hadapan seorang lelaki yang
dicintainya? Sayangnya, aku terlalu buta hingga melupakan aku bukan siapa-siapa
di hadapannya. Merasa kehilangan? Memiliki pun tidak. Segera kusimpulkan bahwa
cinta itu sungguh sangat membutakan.
Beberapa pekan kemudian aku sudah
tidak kembali lagi ke Puskesmas. Hingga pada suatu waktu aku harus kembali ke
sana, tapi tidak bertujuan untuk mengobati diriku yang sakit, melainkan adikku
yang paling bungsu. Perawat itu pun sungguh bingung melihatku, kenapa aku bisa
sehat dan seceria itu? Ia bahkan berpikir kalau aku sudah taken dengannya seperti menikah dengannya atau malah sudah move on
benaran.
Alis mataku terangkat seketika, “aku
menerimanya Bu. Kuterima perasaanku apa adanya, kuterima bahwa aku memang
mencintainya.” Sejak saat itu, racun yang membuatku menjadi sakit kini menjadi
obat bagiku bahkan sesekali menjadi amunisi. Aku berusaha memahami emosional di
masa lalu. Justru perasaan benci itu berangsur-angsur menjadi cinta dengan
sendirinya secara sadar. Kalau enggak disadari mungkin aku sudah menjadi
tengkorak. Kan berat badan turun sekilo dalam rentang satu minggu.
Hadirnya
sudah sangat lama
Namanya cinta, sudah jelas dong
membutakan. Alasan paling signifikan kenapa aku menolak perasaanku dengannya
adalah aku sudah memiliki perasaan mendalam dengan orang sebelumnya. Meskipun
aku mengetahui bahwa aku ditolak mentah-mentah, dijauhi secara halus,
diperlihatkan secara nyata ia dengan gebetannya. Toh aku bahagia saja karena
kupikir syarat untuk mencintai adalah tidak menuntut apa-apa dan tidak menuntut
pula balasan. Alasan paling klasiknya begini, bahagia ketika melihat orang
dicintai bahagia.
Namun yang satu ini, aku tidak
mengenalinya. Jika tidak mengumpulkan buku agendaku dan kubuka satu per satu. Mungkin
aku tidak akan pernah tahu, bahwa dia adalah manusia yang kusebut dengan Jauzi
di masa silam. Jauh sebelum aku berinteraksi secara nyata dengannya. Jauh
sebelum aku menyatakan bahwa aku siap menikah. Ah, ahlinya kisah mengagumi
dalam diam adalah aku. Singkatnya, dia itu sebenarnya pelengkap ide episode
ceritaku yang lengkap dan penyelesaian masalahku dengan tenang. Kuperhatikan sekali
lagi semua ide novelku. Rata-rata aku mengagumi orang, mengabadikan
momentumnya, tapi tak kunjung selesai kutulis. Sedangkan dengannya, ideku
berhamburan. Bahkan novel itu bisa kuselesaikan dalam sebulan. Aneh ya, tapi
nyata. Bahkan dengan tidak berinteraksi sekalipun ia sudah seberdampak itu.
Bersambung
Keterangan :
Congok : banyak makan